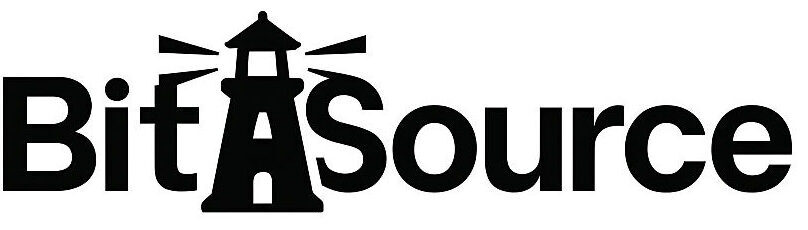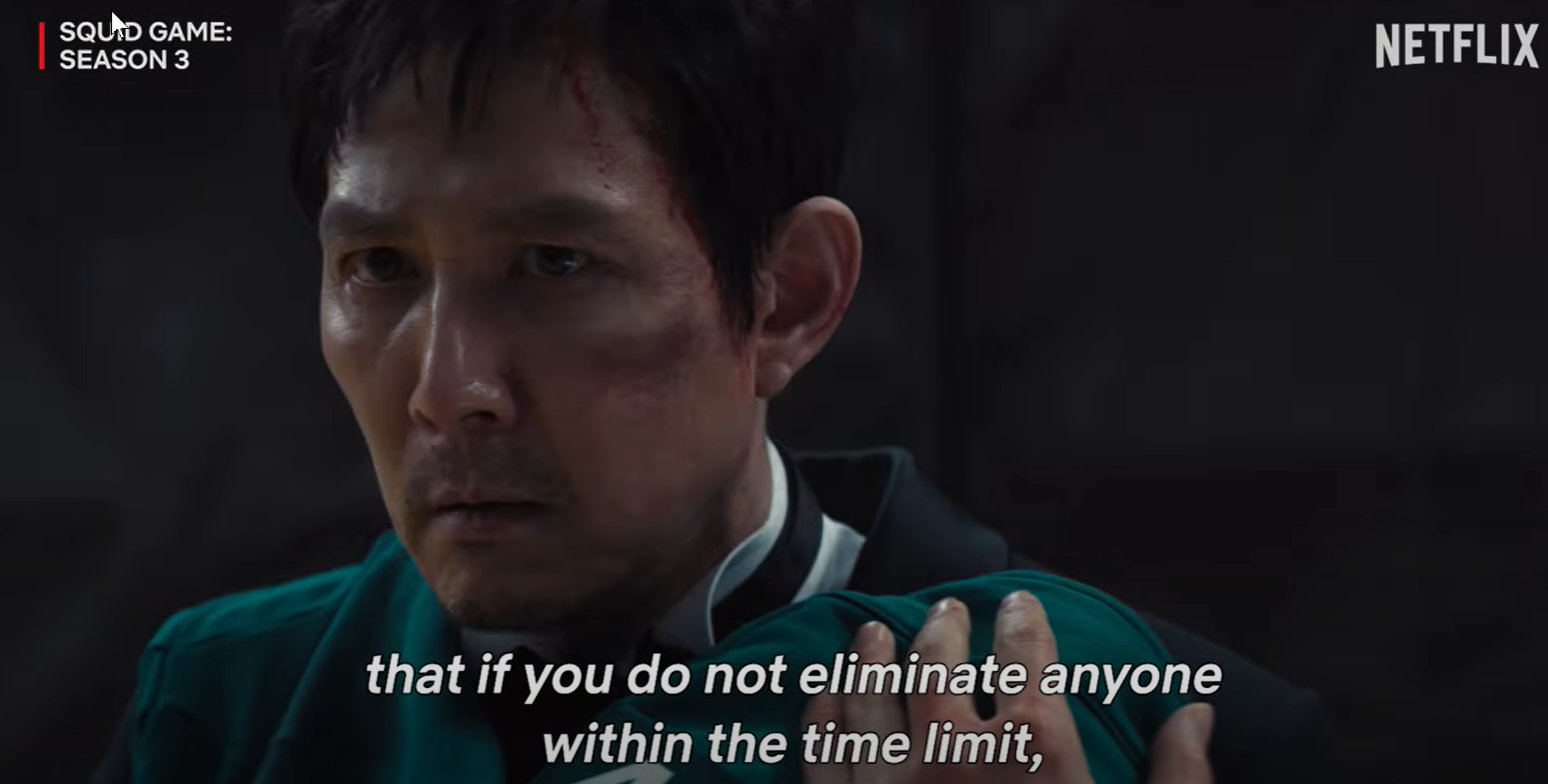“KESALAHAN MEREKA HANYA SATU: PULANG KE INDONESIA!” adalah judul yang tajam dari tulisan Peter F. Gontha, sebuah refleksi yang menyentil tentang ironi di balik harapan terhadap putra-putri terbaik bangsa. Tulisan tersebut menyoroti bagaimana banyak talenta Indonesia yang bersinar di kancah global, setelah menyerap nilai-nilai integritas dan profesionalisme tinggi dari universitas-universitas terkemuka dunia, justru merasa enggan atau bahkan terancam ketika kembali ke tanah air. Mereka yang diharapkan membawa perubahan, seringkali harus berhadapan dengan “kekasaran sistem” yang justru mematahkan niat baik mereka.
Indonesia kaya akan sumber daya manusia cerdas. Setiap tahun, ratusan anak muda kita menembus institusi pendidikan kelas dunia seperti Harvard, Oxford, atau MIT. Mereka kembali dengan bekal ilmu mutakhir, semangat inovasi, dan integritas tinggi. Namun, bukannya disambut dengan karpet merah dan ruang berkreasi, sebagian dari mereka justru menghadapi kenyataan pahit: sebuah sistem yang seolah tidak siap menerima idealisme dan standar tinggi yang mereka bawa. Fenomena ini memicu pertanyaan krusial: mengapa talenta-talenta terbaik bangsa ini justru merasa pulang adalah sebuah risiko?
Diagnosa Sistemik: Jebakan Tata Kelola Amburadul
Peter F. Gontha dengan gamblang menyebutkan “kesalahan mereka hanya satu: pulang ke Indonesia.” Ini bukan sekadar sentimen, melainkan refleksi dari pola yang terlihat pada beberapa kasus nyata, mencerminkan tata kelola yang amburadul dan kurangnya meritokrasi.

Ambil contoh Thomas Lembong, ekonom kelas dunia lulusan Harvard yang sempat menjadi menteri dan berusaha menjaga integritas, namun kemudian namanya terseret dalam kasus hukum yang publik anggap janggal. Ada pula Hotasi Nababan, profesional berintegritas tinggi yang tersandung kasus hukum di BUMN. Menurut Gontha, ini bukan karena niat buruk pribadi melainkan karena sistem yang tidak mendukung atau bahkan menjebak.
Kasus-kasus ini diperparah dengan contoh lain yang sempat menjadi sorotan publik. Arcandra Tahar, ahli migas berkelas dunia yang lulusan Texas A&M University, dicopot dari jabatannya sebagai Menteri ESDM hanya dalam 20 hari karena isu dwi-kewarganegaraan. Meskipun keahliannya diakui dan ia kemudian kembali berkontribusi, insiden itu menunjukkan betapa kaku dan “brutal”-nya sistem kita terhadap detail administratif yang kompleks.
Bahkan figur seperti Nadiem Makarim, lulusan Harvard Business School yang sukses membangun Gojek dan kemudian menjabat Menteri Pendidikan, tak luput dari tantangan sistemik ini. Meskipun membawa semangat Merdeka Belajar dan terobosan, ia juga menghadapi friksi birokrasi, kritik keras, dan yang terbaru, dugaan kasus korupsi pengadaan laptop yang menyeret nama kementeriannya. Demikian pula Gita Wirjawan, yang meskipun sukses berkarir di sektor publik dan swasta, tetap merasakan dinamika politik dan birokrasi yang seringkali tidak sejalan dengan standar global.
Lingkungan profesional dan politik di Indonesia seringkali diwarnai oleh:
- Birokrasi yang beku dan berbelit: Menghambat inovasi dan efisiensi.
- Budaya feodal dan kronisme: Promosi dan jabatan seringkali berdasarkan senioritas atau kedekatan, bukan meritokrasi. Talenta muda yang visioner dianggap ancaman bagi status quo jaringan lama.
- Politik transaksional dan korupsi: Keputusan didasarkan pada kepentingan pribadi, ditambah dengan praktik pengadaan barang dan jasa yang tidak teratur, sarat sogokan, dan intervensi kekuasaan. Vendor dimenangkan karena menyuap, bukan karena kualitas terbaik, mengakibatkan pemborosan anggaran negara dan kualitas proyek yang buruk.
- Sistem hukum yang bisa dipelintir: Penegakan hukum yang selektif dan mudah dimanipulasi oleh kekuasaan atau kepentingan tertentu, seringkali menjerat pihak yang jujur.
Hal ini juga tercermin di sektor-sektor spesifik. Misalnya, dokter lulusan universitas top di Singapura, AS, Inggris, atau Australia seringkali kesulitan berpraktik di Indonesia karena regulasi adaptasi yang rumit, masalah pengakuan gelar, serta kekuatan profesi yang membatasi masuknya keahlian baru. Mereka yang telah menyerap ilmu canggih dari luar negeri justru tidak mendapat tugas yang sesuai, dijegal senior, dan tidak mendapatkan gaji memadai, jauh berbeda dengan meritokrasi di negara seperti Singapura.
Ajakan Reformasi: Mencegah ‘Heart Drain’

Melihat kondisi ini, sudah saatnya kita menyadari bahwa negara ini harus berubah. Reformasi bukan hanya tentang ekonomi atau birokrasi, tetapi yang lebih fundamental, tentang cara negara ini memperlakukan integritas dan talenta terbaiknya. Kita tidak bisa membiarkan narasi bahwa pulang ke Indonesia adalah risiko tertinggi bagi profesional muda yang ingin berbuat baik.
Seharusnya, negara merangkul mereka, bukan mencurigai; menjaga mereka, bukan memenjarakan; dan mendorong mereka untuk membangun, bukan menakut-nakuti mereka agar tidak kembali. Sistem harus adaptif, transparan, dan meritokratis. Jika tidak, “brain drain” yang sudah menjadi masalah akan berubah menjadi “heart drain” – bukan hanya otak yang pergi, tapi juga hati dan harapan.
Tantangan untuk Pemimpin: Melindungi Integritas Bangsa
Ini adalah tantangan langsung bagi kepemimpinan nasional. Presiden, parlemen, aparat penegak hukum, dan para pemimpin BUMN harus menjawab pertanyaan krusial: Mau dibawa ke mana negeri ini jika orang-orang terbaiknya terus dipatahkan oleh sistemnya sendiri? Jika seorang lulusan Harvard atau profesional kelas dunia takut pulang karena takut dikriminalisasi, terjebak dalam masalah birokrasi, atau dijegal oleh kronisme, maka ada yang sangat salah dalam cara kita membangun bangsa ini.
Kita harus menciptakan iklim yang tidak hanya menghargai kepintaran, tetapi juga melindungi integritas dan memberikan ruang bagi mereka yang ingin bekerja dengan benar, tanpa rasa takut. Ini berarti menegakkan meritokrasi sejati, memberantas korupsi di segala lini termasuk pengadaan, dan menyederhanakan regulasi agar tidak menjadi penghalang bagi kontribusi talenta terbaik.
Penutup dan Refleksi
Kita tidak boleh membiarkan generasi muda Indonesia yang kini menimba ilmu di luar negeri berpikir bahwa kesalahan terbesar mereka adalah jika suatu hari mereka memutuskan untuk pulang. Jika itu terjadi, kita bukan hanya kehilangan potensi besar, tetapi juga masa depan bangsa ini. Mari kita ciptakan Indonesia yang benar-benar menjadi rumah bagi setiap anak bangsanya, tempat di mana integritas dan niat baik dihargai, bukan dipatahkan. Kita membutuhkan sebuah revolusi dalam tata kelola untuk memastikan bahwa pulang ke Indonesia adalah sebuah kehormatan dan kesempatan, bukan sebuah risiko.